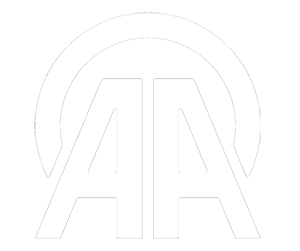Ilustrasi: Seorang polisi bermain dengan anak-anak pengungsi dari berbagai daerah di Papua di Gedung Olah Raga Merauke. Mereka mengungsi setelah kawasan tempat tinggalnya dilanda kerusuhan. (Muhammad Abdul Syah - Anadolu Agency)
Ilustrasi: Seorang polisi bermain dengan anak-anak pengungsi dari berbagai daerah di Papua di Gedung Olah Raga Merauke. Mereka mengungsi setelah kawasan tempat tinggalnya dilanda kerusuhan. (Muhammad Abdul Syah - Anadolu Agency)
Jakarta Raya
JAKARTA
Suasana Papua lebih panas dari biasanya dalam tiga bulan terakhir, setelah puluhan orang tewas dalam kerusuhan yang dipicu isu rasialis dan diskriminasi terhadap penduduk asli provinsi di ujung timur Indonesia ini.
Sejak itu, tuntutan referendum dan slogan-slogan pro-kemerdekaan – yang sebenarnya tak pernah padam – seperti menemukan momentum untuk kembali bersuara bahkan lebih nyaring.
Sementara, Jakarta merespons dengan mengirimkan lebih banyak pasukan keamanan.
Papua, provinsi yang berpenduduk asli ras Melanesia, syarat dengan sejarah pelanggaran ham, persaingan bisnis dan konflik politik, terutama sejak Indonesia dipimpin presiden Suharto pada akhir 1960-an.
Masuknya provinsi ini menjadi bagian dari Indonesia ini adalah kelindan antara kepentingan negara-negara besar pada awal perang dingin, kepentingan bisnis, serta pembagian wilayah kekuasaan negara-negara baru merdeka.
Referendum yang penuh pertanyaan
Indonesia yang merdeka pada 1945 menginginkan semua bekas wilayah jajahan pemerintahan kolonialisme Belanda menjadi wilayahnya, termasuk Papua yang kala itu disebut sebagai Netherlands New Guinea.
Namun, Belanda tidak bersedia memberikan wilayah ini karena secara ras dan etnis orang Papua asli berbeda dengan kebanyakan pendudukan Indonesia.
Sengketa ini berlangsung sejak Konferensi Meja Bundar (KMB) pada 27 Desember 1949 hingga belasan tahun kemudian.
M.C. Ricklefs dalam “Sejarah Indonesia Modern” (2008), mengatakan dengan difasilitasi Amerika Serikat tercapai kesepakatan antara Indonesia dan Belanda tentang Papua yang disebut dengan “Perjanjian New York” pada 15 Agustus 1962.
Inti kesepakatan adalah Belanda menyerahkan Papua di bawah kendali Otoritas Eksekutif Sementara PBB (UNTEA) pada 1 Oktober 1962. Selanjutnya, Belanda harus menyerahkan Papua bagian barat kepada Indonesia selambat-lambatnya pada 1 Mei 1963.
“Sebelum akhir 1969, Jakarta juga akan menyelenggarakan pemilihan yang bebas di Papua untuk mengetahui apakah penduduknya menghendaki tetap menjadi bagian dari Indonesia atau tidak,” tulis Ricklefs.
Sejak perjanjian ini diteken, sudah muncul suara-suara yang menentang, karena tidak ada orang asli Papua yang dilibatkan dalam perundingan.
Pada 14 Juli hingga 2 Agustus 1969, akhirnya Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) atau Act of Free Choice digelar sebagai referendum menentukan apakah penduduk Papua menghendaki tetap bergabung dengan Indonesia atau tidak.
Referendum tersebut diikuti oleh 1.026 anggota Dewan Musyawarah Pepera (DMP) yang mewakili 815.904 penduduk Papua.
Anggota DMP terdiri dari 400 orang kepala suku dan adat, 360 orang dari unsur daerah, 266 orang dari unsur organisasi masyarakat.
DMP kemudian memilih agar Papua menjadi bagian dari Republik Indonesia.
Namun sebagian masyarakat Papua merasa hasil Pepera tidak mewakili keinginan mereka yang seutuhnya.
Mereka memelesetkan referendum, dari “act of free choice” menjadi “act of no choice“ karena mereka dipaksa dengan ancaman kekerasan militer untuk memilih Indonesia.
Fakta lain adalah, sebelum referendum digelar, Pemerintah Indonesia dibawah Presiden Soeharto --yang berhasil mengambil kekuasaan dari Presiden Soekarno-- sudah menandatangani kontrak karya dengan perusahaan asal Amerika Serikat Freeport untuk memulai kegiatan kegiatan penambangan emas di Ertsberg, Puncak Jaya.
Kepala Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari Yan Warinussy mengatakan hasil referendum 1969 yang tidak representatif selalu menjadi ganjalan masyarakat Papua dalam menjalani integrasinya dengan Indonesia.
“Bahkan di dalam (referendum) ada orang-orang non-Papua yang terlibat. Inilah yang menjadi persoalan yang selalu diperdebatkan dari waktu ke waktu. Referendum 1969 tidak pernah bisa merepresentasikan keinginan masyarakat Papua,” ujar dia.
Warinussy menekankan bahwa pemerintah Indonesia perlu “meluruskan” sejarah Papua yang dimulai sejak referendum, agar tidak lagi menjadi ganjalan yang terus memicu konflik-konflik dan ketidakpuasan di Papua.
Legalitas Pepera kuat
Menurut Juru Bicara Kementerian Luar Neger Indonesia Teuku Faizasyah, hasil Pepera 1969 sudah sangat kuat.
Jajak pendapat itu, kata Faizasyah, digelar atas kesepakatan Indonesia-Belanda dan PBB, dengan mekanisme dan aturan-aturan yang sudah disepakati, termasuk sistem perwakilan.
Menurut dia, sistem perwakilan bahkan masih tetap relevan dengan kondisi kontemporer, karena masyarakat Papua hingga kini mengenal sistem “noken” – yang memperbolehkan perwakilan dalam mencoblos surat suara – dalam Pemilu maupun Pilkada.
“Hasilnya dibawa ke Majelis Umum PBB dan diterima. Jadi pertanyaan-pertanyaan soal Pepera sangat tidak beralasan,” ujar dia.
Pepera, menurut Faizasyah, adalah kesepakatan politik antara Indonesia-Belanda, setelah sebelumnya Indonesia mewarisi bekas tanah jajahan Hindia Belanda, dari Sabang sampai Merauke.
“Setelah perjanjian KMB seharusnya Papua diserahkan ke Indonesia. Tapi Belanda tidak melakukannya, akhirnya ada proses politik,” ujar dia.
Menurut dia, sejak awal Papua adalah bagian dari Indonesia, karena merupakan daerah koloni Hindia Belanda yang harus diserahkan begitu muncul negara baru.
“Itu prinsip hukum internasional,” kata Faizasyah.
Hal serupa terjadi di Afrika, sehingga mereka kini terpisah dalam negara-negara kecil meski secara sebenarnya secara etnis dan budaya mempunyai banyak kesamaan.
“Afrika dijajah banyak negara. Sehingga setelah merdeka mereka terpisah oleh garis kecil-kecil yang disepakati negara penjajah,” ujar dia.

Perlawanan dan pelanggaran HAM di Papua
Ketidakpuasan penduduk Papua ini memicu perlawanan yang lebih serius dengan membentuk gerakan politik militer yang sering disebut sebagai Organisasi Papua Merdeka (OPM).
Perlawanan bersenjata mereka pecah untuk pertama kalinya pada 26 Juli 1965 di Manokwari.
Menurut laporan Institute for Policy Analysis of Conflict (IPAC) berjudul The Current Status of The Papuan Pro-Independence Movement, kegiatan penambangan Freeport pada 1973 memicu aktivitas militer OPM di wilayah Timika.
Kemudian pada Mei 1977, sekitar 200 gerilyawan OPM menyerang Freeport dan direspons dengan operasi militer, terutama di Desa Amungme.
Tanah Freeport sendiri dulunya merupakan tanah adat suku Amungme dan Komoro yang merupakan penduduk asli di wilayah tersebut.
Direktur Eksekutif United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) Markus Haluk dalam buku “Menggugat Freeport” menyebutkan 60 orang suku Amungme menjadi korban kekerasan militer dalam insiden itu.
Kasus-kasus kekerasan dan pelanggaran HAM terus terjadi di Papua.
Gelombang kekerasan yang terjadi sekitar tiga bulan belakangan mengakibatkan delapan orang sipil tewas di Deiyai dalam kerusuhan pada 28 Agustus 2019.
Kemudian, kerusuhan lain terjadi pada 26 September 2019 mengakibatkan 33 orang tewas di Wamena dan empat orang tewas di Jayapura.
Tragedi mengenaskan lainnya terjadi pada 2 Desember 2018 yang menewaskan 31 pekerja proyek jalan raya Trans Papua tewas ditembaki di wilayah Nduga oleh kelompok bersenjata Papua pimpinan Egianus Kogoya.
Peristiwa itu dijawab dengan operasi militer di wilayah Nduga.
Amnesty International Indonesia mencatat 182 warga sipil Nduga meninggal dalam pelarian diri, setelah kampung mereka didatangi aparat keamanan yang memburu kelompok Egianus.
Pemerintah juga masih memiliki utang untuk menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM di Papua, seperti kasus Wasior pada 2001 dan kasus Wamena pada 2003 yang lagi-lagi disebabkan konflik aparat dengan warga setempat.
Jakarta menuding tokoh pro-kemerdekaan Papua, Benny Wenda, menjadi dalang kerusuhan di Bumi Cendrawasih tiga bulan belakangan.
“OPM dan Benny Wenda berusaha membangun suatu kerusuhan dan ekspose ke dunia luar ada kekuatan untuk memerdekakan Papua dan Papua Barat,” kata mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Wiranto pada 30 September lalu.
Yan Warinussy mendesak pemerintah menyelesaikan akar permasalahan Papua dan menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM. Menurut dia, kerusuhan yang terjadi di Papua tiga bulan belakangan merupakan buntut dari gagalnya pemerintah menangani kasus rasialis.
“Kasus pelaku rasialis dan diskriminasi itu sampai saat ini tidak jelas prosesnya,” kata Warinussy ketika dihubungi.
“Berkali-kali Presiden Jokowi ke Papua, tapi persoalan pelanggaran HAM belum pernah disentuhnya,” tutur Warinussy.

Menunggu tangan dingin Jokowi di Papua
Publik menunggu langkah-langkah Presiden Joko Widodo pada periode kedua pemerintahannya untuk menyelesaikan masalah Papua.
Harapan semakin kuat setelah dia meresmikan Jembatan Youtefa di Jayapura, yang merupakan kunjungan ke daerah pertama setelah dia menjabat presiden.
Tapi lagi-lagi pemerintah hanya melakukan pendekatan ekonomi, dengan terus membangun infrastruktur di Papua.
"Kedatangan saya di Papua saat ini merupakan ke-13 kali dan kita bertekad untuk membangun Papua yang lebih maju," ujar Jokowi, sapaan akrab presiden pada 28 Oktober 2019.
Usai kunjungan itu, pemerintah memastikan akan melakukan pemekaran wilayah di Papua. Papua yang tadinya terdiri atas dua provinsi, yakni Papua dan Papua Barat akan dimekarkan menjadi total empat provinsi.
Pemerintah mengklaim pemekaran provinsi di Papua akan membuat pengelolaan pembangunan lebih efektif, selain membangun iklim politik yang lebih kondusif. Keputusan ini juga diklaim sebagai respons atas aspirasi tokoh Papua.
Pendekatan ekonomi sebenarnya sudah dilakukan pemerintah sejak lama.
Dengan payung UU Otonomi Khusus, pemerintah membanjiri dana sebesar USD5,3 miliar atau sekitar Rp75,4 triliun sejak 2002-2009.
Namun dana berlimpah ruah itu tidak berarti banyak. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Papua versi Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2018 hanya 60,06, menempati peringkat terbawah sekaligus jauh tertinggal ketimbang wilayah lainnya.
Koordinator Jaringan Damai Papua Adriana Elisabeth mengatakan pemekaran wilayah dan menggelontorkan dana dalam jumlah yang sangat besar tidak cukup menyelesaikan konflik di Papua.
Menurut Adriana yang juga peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), pemekaran wilayah hanya akan memuaskan elite dan kelompok tertentu di Papua tanpa menyentuh akar persoalan.
LIPI sudah sejak lama memetakan empat akar persoalan di Papua. Yakni kegagalan pembangunan, marginalisasi dan diskriminasi orang asli Papua, kekerasan negara dan pelanggaran HAM, serta sejarah dan status politik wilayah Papua.
“Pemekaran wilayah mudah dilakukan. Tapi apakah itu menjamin konflik demografi di tengah masyarakat Papua hilang?”
“Kalau tidak diselesaikan hingga akar persoalannya, tetap akan terbawa.”
Menurut Adriana, pembangunan ekonomi tetap perlu dilakukan, tapi pemerintah juga harus memastikan orang asli Papua bisa dapat merasakan dan memiliki daya beli terhadap infrastruktur yang dibangun.
Karena selama ini, roda perekonomian di Papua justru “dikuasai” oleh warga pendatang.
Masih banyak orang asli Papua yang tinggal di wilayah pedalaman dan belum tersentuh pendidikan dan pelayanan kesehatan yang layak.
Sedangkan kasus-kasus kekerasan yang terus berulang di Papua juga harus segera diselesaikan.
Perlu ada dialog untuk menghentikan rantai kekerasan di Bumi Cendrawasih, meski tidak musti membahas status politik Papua atau aspirasi referendum, setidaknya bahas bagaimana menghentikan kekerasan di Papua, tutur Adriana.
Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP) Timotius Murib meminta pemerintah tidak menutupi masalah HAM di Papua dengan proyek-proyek pembangunan infrastruktur.
“Pembangunan menjadi kewajiban negara di seluruh Indonesia. Tapi harus ada prioritas di Papua yaitu bicara masalah HAM,” kata dia.
Masyarakat Papua, lanjut Timotius, menanti komitmen Jokowi menuntaskan kasus HAM pada lima tahun terakhir, namun belum terbukti hingga kini.
“Tidak satu pun beliau sentuh dan bicarakan dalam lima tahun terakhir,” tutur dia.
Selain itu, dia mendesak pemerintah fokus membangun sumber daya manusia Papua. Dia juga mengatakan rencana pemekaran wilayah di Papua tidak dibutuhkan masyarakat.
“Kalau hanya membangun infrastruktur dasar terkesan membangun tanah Papua tapi tidak membangun manusianya,” ujar Timotius.
Victor Mambor, seorang wartawan di Papua mengatakan konflik Papua membutuhkan solusi komprehensif mulai dari pelurusan sejarah, penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM dan masalah demografi bukan sekadar mewujudkan kesejahteraan “ala Jakarta”.
Dengan pandangan ini, kemudian lahir kebijakan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur sehingga diharapkan perekonomian tumbuh lebih tinggi. Pendekatan ini sudah dilakukan sejak era Presiden Soeharto dan terbukti tidak berhasil.
“Meski penting, tapi tidak pembangunan infrastruktur tetap menyentuh akar konflik di Papua,” ujar dia.
Untuk menyelesaikan konflik pemerintah harus berbesar hati mengakui bahwa ada kelompok bersenjata yang menginginkan kemerdekaan. Mereka bukan kelompok kriminal bersenjata, penyebutan yang kerap dilakukan pemerintah, namun memiliki ideologi dan aspirasi politik.
“Penyelesaiannya tentu akan berbeda. Memandang kelompok itu hanya sebagai gerombolan kriminal tidak akan menyelesaikan persoalan,” ujar dia.
Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Budiman Sudjatmiko mengatakan masalah Papua harus diselesaikan dengan jalan damai dan mengedepankan dialog yang dimulai dari tingkat suku-suku.
“Papua belum menjadi bangsa yang terpisah dari Indonesia, sementara referendum tidak dimungkinkan dalam aturan perundangan,” ujar dia dalam sebuah diskusi di Jakarta.
“Harus ada jalan damai bagi Papua. Pendekatan militerisme harus dihilangkan. Orang-orang Papua harus terus menerus memberi kepercayaan dengan kelembagaan tadi dan menciptakan dialog.”
Teuku Faizasyah mengatakan tuntutan referendum tidak kontekstual, karena masalah Papua sebenarnya adalah urusan politik yang sudah diselesaikan.
“Papua itu hanya tertunda bergabung dengan Indonesia, itu warisan dari kolonialisme.“
Website Anadolu Agency Memuat Ringkasan Berita-Berita yang Ditawarkan kepada Pelanggan melalui Sistem Penyiaran Berita AA (HAS). Mohon hubungi kami untuk memilih berlangganan.