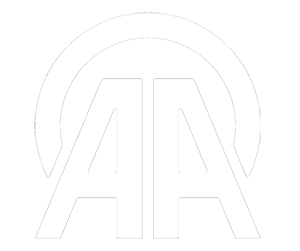Menjejaki kebudayaan Tionghoa di Jakarta
Jejak kedatangan Tionghoa di ibu kota sejak lebih dari 3 abad lalu masih banyak berdiri hingga kini
 Seorang pengunjung bersembahyang di Vihara Dharma Bhakti, Glodok, Jakarta Barat, 12 Februari 2018. (Megiza Asmail - Anadolu Agency)
Seorang pengunjung bersembahyang di Vihara Dharma Bhakti, Glodok, Jakarta Barat, 12 Februari 2018. (Megiza Asmail - Anadolu Agency)
Megiza Asmail
JAKARTA
Dari lima wilayah di ibu kota, kawasan Jakarta Barat dan Utara memang lebih identik dengan permukiman warga Tionghoa di Ibu Kota. Karenanya, tidak heran jika tiap-tiap perayaan Imlek, dua wilayah tersebut menunjukkan euforia tahun baru China yang lebih besar dibanding masyarakat di kawasan Jakarta yang lain.
Beberapa buku menuliskan banyaknya masyarakat Tionghoa yang tersebar di dua wilayah itu dikarenakan berdekatan dengan perbatasan Banten, tepatnya Tangerang.
Pemerhati kebudayaan yang juga ketua tim pemugaran salah satu situs peninggalan Tionghoa di Jakarta Naniek Widayati menyebut kedatangan etnis China di Indonesia pertama kali dibawa oleh Belanda untuk dijadikan buruh tanam.
Sekitar abad 13-an, kata Naniek, masyarakat di wilayah selatan China berada dalam kondisi miskin. Mereka bedol desa dibawa Belanda ke Indonesia untuk dijadikan buruh bercocok tanam rempah-rempah.
Maluku kemudian menjadi basis utama Belanda memulai hidup di Nusantara. Masyarakat China pun dimigrasikan ke Indonesia pertama kali ke sana. Selain Maluku, warga Tiongkok yang migrasi ada juga yang mendarat di Singkawang, Kalimantan.
Hidup menjadi buruh, warga Tiongkok kemudian terseret ke Jawa. Pasalnya, Belanda kala itu ingin membawa barang dagangan rempah mereka ke dataran Jawa. Sebagian dari warga Tiongkok itu dipindahkan dari wilayah timur Indonesia ke bagian barat.
“Barang-barang itu dibawa ke Jawa. Pelabuhan pertamanya itu di Banten, dengan pelabuhan landing di Karangantu,” kata Naniek saat berbincang dengan Anadolu Agency.
Namun, karena Raja yang berkuasa di Banten saat itu cerdas dan selalu menaikkan pajak (ongkos kapal mendarat), Belanda kemudian berpikir untuk membuat pelabuhan sendiri. Hingga akhirnya tergiur dengan kawasan Jayakarta.
Pelabuhan Sunda Kelapa, disebut Naniek, dibangun sebagai pintu masuk lain perdagangan mereka ke tanah Jawa. Dalam pembangunannya, Belanda mengalami kesulitan untuk berkomunikasi dengan masyarakat lokal.
Lagi-lagi, warga Tionghoa yang ‘dipindahkan’ oleh Belanda pun dimanfaatkan. Mereka dijadikan sebagai perantara berkomunikasi.
“Belanda melihat masyarakat pribumi yang ada di kawasan yang sekarang disebut Kota Tua itu, susah untuk berkomunikasi dengan mereka. Sehingga orang-orang China yang didatangkan menjadi perantara komunikasi Belanda dengan masyarakat lokal,” ujar Naniek.
Setelah berhasil membangun pelabuhan dan kota, Belanda kemudian ingin membangun benteng. Namun, masalah baru datang. Warga Tiongkok yang dibawa mereka ternyata beranak-pinak dengan sangat cepat.
“Menjadi problem ketika orang-orang China yang dibawa itu cepat sekali berkembang biaknya. Sehingga kapasitas orangnya menjadi banyak. Dan mereka kan lebih pintar daripada lokalnya, Belanda pun mulai khawatir,” tutur Naniek.
Warga Tiongkok akhirnya dipindahkan dari pusat kota (Kota Tua) ke kawasan Selatan. Dengan menggunakan sistem grade permukiman ala Belanda, mereka berpindah ke kawasan yang sekarang dikenal dengan nama Petak Sembilan, Roa Malaka, Tambora dan Glodok.
“Kawasan itu dibuat untuk mengonsentrasikan orang China supaya gampang dikendalikan,” imbuh Naniek.
Sayangnya, pemberontakan kemudian terjadi. Puncaknya, sekitar 10 ribu orang China, kata Naniek, dibunuh pada tahun 1740. Di Kali Angke jasad mereka dibuang.
Berbagai cara dilakukan oleh Belanda untuk mengatur warga lokal dan juga migran asal Tiongkok yang dibawanya ke tanah Jawa. Salah satu taktik lain adalah dengan membuat konsensus dengan orang-orang Tiongkok yang pandai dan sudah kaya.
“Belanda mulai berpikir harus ada pemimpin untuk mengendalikan mereka. Maka muncullah Kapitan China dan Mayor China. Itu sebenarnya jabatan yang diberikan Belanda kepada orang China yang pandai, kaya, dan pro-Belanda, untuk mengendalikan bangsanya dalam wilayah dia,” tutur dia.
Salah satu Mayor yang terkenal kala itu adalah Mayor Khouw Kim An. Kediamannya yang dibangun dengan menggunakan sistem kasta bak pangeran China masih berdiri tegak hingga kini di Jalan Gadja Mada Nomor 188 Jakarta Pusat. Chandra Naya, nama bangunan itu.


Peninggalan muslim Tionghoa di Jakarta
Membaca jejak Tionghoa di ibu kota memang tak hanya dapat dilakukan melalui melihat pemetaan permukiman atau rumah tinggal. Banyak bangunan tempat ibadah peninggalan mereka yang masih berdiri dengan tegak hingga kini. Vihara Dharma Bhakti di Petak Sembilan, Glodok, misalnya.
Rumah ibadah yang dibangun pada tahun 1650 oleh Letnan Guo Xun Guan dengan nama Guan Yin Ting itu masih terus hidup hingga saat ini. Memang, pada peristiwa 1740, vihara ini sempat dibakar oleh Belanda saat terjadi pembantaian etnis.
Namun, Kapiten Oey Tjie merekonstruksinya di tahun 1755. Namanya berganti menjadi Jin De Yuan atau Kim Tek Ie. Hingga kini, kelenteng Kim Tek Ie dan permukiman di sekitarnya menjadi salah satu peninggalan jejak Tionghoa di Jakarta.
Di sisi lain, etnis Tionghoa yang tinggal di ibu kota juga memiliki masjid sebagai tempat ibadah. Masih di kawasan Glodok, sebuah masjid tua yang dibangun oleh orang-orang keturunan Tionghoa ada di sini.
Masjid Jami Kebon Jeruk, namanya. Masjid yang berada di Jalan Hayam Wuruk Nomor 83 ini, menurut beberapa catatan, didirikan pada tahun 1786 oleh muslim keturunan Tionghoa sebagai rumah ibadah pertama.
“Masjid Kebon Jeruk itu itu adalah situs awal pengembangan muslim di Jakarta. Didirikan oleh masyarakat China muslim. Kalau muslim Tionghoa hadir di Jakarta bekerja sebagai pedagang,” sebut Naniek.
Meski masih berdiri dengan kokoh dan makam pendirinya masih bersemayam di dalam masjid, Naniek menyebut, paradigma pengelola Masjid Kebon Jeruk saat ini sudah jauh berbeda dengan pendahulunya.
Saat ini, kata dia, kelompok Islam ekstrem menguasai masjid tersebut. Naniek bahkan pernah dilarang masuk oleh penjaga masjid ketika mengunjungi masjid tersebut.
“Situs memang masih ada, utuh. Akan tetapi paradigma pelakunya sudah berbeda. Padahal orang-orang China meyakini agama apapun boleh dianut, asalkan tradisi menghormati roh nenek moyang itu tetap dijaga,” tutur Naniek.
Di Indonesia sendiri agama Konghucu telah kembali diakui menjadi agama Nasional sejak Presiden Abdurrahman Wahid -atau yang akrab disapa Gus Dur- mencabut Instruksi Presiden Nomor 14 tahun 1967 yang dikeluarkan oleh Presiden Soeharto.
Kala itu, Presiden Soeharto menyatakan larangan atas segala hal yang bernuansa Tionghoa, termasuk Imlek.
Gus Dur, yang juga cucu dari pendiri Nahdlatul Ulama KH. Hasyim Asy’ari itu, pada tahun 1999 memberikan kebebasan untuk warga Tionghoa merayakan imlek di muka umum. Pun dengan tradisi-tradisi lain yang boleh kembali dipertunjukkan.
Hujan saat Imlek, tradisi petani China tak berharta
Perayaan tahun baru China memang identik dengan banyak hal. Mulai dari bersembahyang di kelenteng, hingga atraksi Barongsai dan Liong terlihat di berbagai tempat pada perayaan Imlek 2569 yang jatuh pada hari ini.
Berbagai pemuka agama menegaskan Imlek memang bukan perayaan agama.
Sama dengan pergantian tahun di akhir Desember, warga Tionghoa merayakan Imlek sebagai tradisi menyambut tahun yang baru.
“Tradisi di China, Imlek itu hanya sebuah hari bahagia. Cuma mereka dulunya, masyarakat China yang kebanyakan petani itu berharap hujan pada saat tahun baru. Karena mereka mengidentikkan hujan dengan rezeki yang banyak di tahun yang akan datang,” kata Naniek.
Website Anadolu Agency Memuat Ringkasan Berita-Berita yang Ditawarkan kepada Pelanggan melalui Sistem Penyiaran Berita AA (HAS). Mohon hubungi kami untuk memilih berlangganan.