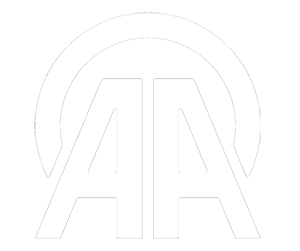Ankara, Turki
Ahmet Sait Akcay dan Cansu Dikme
ANKARA
Konflik di Negara Bagian Rakhine di Myanmar mempertegas peran militer dalam politik dan menghambat perkembangan transisi demokrasi di negara tersebut, ujar seorang pakar politik Amerika kepada Anadolu Agency.
Sejak 25 Agustus lalu, sekitar 515.000 warga Rohingya menyeberang dari Rakhine, Myanmar, menuju Bangladesh, menurut PBB.
Para pengungsi tersebut melarikan diri dari operasi militer, di mana pasukan keamanan membunuh laki-laki, perempuan dan anak-anak, menjarah tumah serta membakar desa.
Menurut Menteri Luar Negeri Bangladesh Abul Hasan Mahmood Ali, sekitar 3.000 Rohingya terbunuh dalam aksi kekerasan tersebut.
Nehginpao Kipgen, asisten professor dan Direktur Eksekutif Pusat Studi Asia Tenggara (Centre for Southeast Asian Studies) dari Sekolah Urusan Internasional JindaI di India mengatakan bahwa kekerasan di Myanmar menunjukkan fakta bahwa transisi di Myanmar menuju demokrasi seutuhnya masih beberapa dekade lagi.
“Kekerasan di Rakhine dan tantangan yang dihadapi proses perdamaian pemerintah dengan kelompok bersenjata di negara tersebut tampaknya menunjukkan bahwa militer akan terus menunjukkan perannya dalam persoalan politik maupun keamanan.
“Dengan kata lain, transisi Myanmar menuju demokrasi penuh atau mapan butuh waktu bertahun-tahun, jika bukan decade,” kata dia.
Isu Rohingya, kata dia, akan terus mengancam keamanan dan wilayah, jika persoalan kewarganegaraan dan identitas tetap tak terselesaikan.
Lebih lanjut ia mengatakan bahwa rakyat Myanmar juga harus menerima kenyataan.
“Penting agar warga Myanmar memahami bahwa tanpa menangani persoalan mendasar dari Rohingya, seperti identitas dan kewarganegaraan, isu Rohingya akan terus menjadi ancaman keamanan dan wilayah,” katanya.
Membahas akar masalah
Kipgen juga mengingatkan bahwa isu tersebut akan menghambat proses perdamaian dan pembangunan bangsa.
“Barangkali sulit atau bahkan tak mungkin bagi umumnya warga Burma, termasuk militer dan kelompok ultranasionalis atau nasionalis untuk menerima Rohingya sebagai warga Myanmar,” tambahnya.
“Persoalan mendasarnya adalah baik Pemerintah Myanmar maupun Bangladesh tak mau menerima Rohingya sebagai warganya.”
Mengenai krisis pengungsi yang tengah berlangsung, ia mengatakan bahwa Pemerintah Myanmar dan Bangladesh, selain PBB, dan masyarakat internasional, harus memenuhi kebutuhan mereka.
Kipgen melihat solusi jangka panjang bagi teka-teki Rohingya dalam implementasi rekomendasi komisi Kofi Annan.
“Pemerintah harus mengambil langkah konkret untuk mengakhiri segregasi warga Budha Rakhine dan muslim Rohingya, untuk membahas persoalan tanpa kewarganegaraan Rohingya, dan mengakhiri pembatasan terhadap gerakan pembebasan Rohingya.”
PBB menggambarkan Rohingya sebagai warga paling teraniaya di dunia, yang terus-menerus menghadapi ketakutan sejak puluhan orang terbunuh dalam kekerasan komunal pada 2012.
Oktober lalu, setelah serangan di pos perbatasan Distrik Miangdao, Rakhine, pasukan keamanan melancarkan aksi kekerasan selama lima bulan yang membunuh 400 orang menurut Rohingya.
PBB mencatat perkosaan massal, pembunuhan – termasuk bayi dan anak kecil – pemukulan brutal dan penculikan dilakukan petugas keamanan.
Dalam sebuah laporan, penyidik PBB mengatakan bahwa pelanggaran tersebut merupakan kejahatan kemanusiaan.